Pengetahuan dan Kepentingan Manusia Menelaah Pidato Jürgen Habermas
Oleh: Ismir Lina
Pemerhati Sosial
Pada tahun 1965, Jürgen Habermas—seorang filsuf dan sosiolog Jerman—menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai Profesor di Universitas Frankfurt. Pidatonya itu dimuat dalam sebuah manuskrip bertajuk “Erkenntnis und Interesse”. Pada tahun 1968 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “Knowledge and Human Interests”. Menarik untuk disimak.
Habermas menggambarkan perjalanan genealogis proyek pemurnian ilmu pengetahuan dari kepentingan. Gejalanya dapat ditelusuri kembali ke kelahiran pemikiran filsafat, yang berhasil mengubur gagasan-gagasan mitis dalam kehidupan keagamaan Yunani kuno.
Menurut Habermas, kata “theoria” dalam bahasa Yunani berarti “perenungan” atau “teori” awalnya bermakna ritual keagamaan yang menyiratkan suatu bentuk kehidupan dan cara untuk mengolah serta mendidik jiwa melalui pembebasan umat manusia dari perbudakan doxa (opini dangkal).
Melalui jalan ini, manusia diharapkan mencapai otonomi dan kebijaksanaan dalam hidup. Dalam tradisi keagamaan Yunani kuno, orang yang mempraktikkan theoria disebut theoros (teoritikus), seorang wakil yang diutus oleh polis (negara) untuk keperluan ritual keagamaan.
Jadi seorang teoretikus berupaya mengembangkan theoria, “memandang peristiwa-peristiwa sakral dan terlibat di dalamnya dengan tujuan memungkinkan teoretikus mengalami katarsis momen pembebasan dari ketidakstabilan perasaan dan impuls fana sebuah pengalaman emansipasi dari hasrat-hasrat dasar.”
Dengan kata lain sepanjang sejarah Yunani kuno teori dipahami sebagai pengetahuan yang memiliki daya emansipatoris, karena kedudukannya terletak dalam kehidupan praksis, sehingga cita-cita etis teori selalu berpuncak pada prinsip kemanfaatan dalam kehidupan manusia konkret, yaitu perwujudan kebaikan, kebahagiaan, kebijaksanaan, kebebasan, dan kehidupan sejati dalam kerangka kolektif negara.
Hadirnya Filsafat Ontologi
Demitologisasi pemikiran mitis berlangsung sangat radikal, dimulai dengan munculnya pemikiran filsafat di Yunani kuno. Konsep theoria, atau “memandang”, tidak lagi dipahami dalam kaitannya dengan ritus keagamaan. Sebaliknya, konsep tersebut bergeser menjadi “memandang” dalam arti “kontemplasi kosmos” memandang ke arah alam semesta.
Para filsuf sejak Parmenides dan diperkuat oleh Plato berusaha menemukan tatanan yang tak berubah atau makrokosmos, di mana manusia sebagai mikrokosmos, sekadar melakukan tindakan mimesis (meniru) terhadap tatanan yang tak berubah di dalam makrokosmos. Theoria—yang kini dipahami sebagai “kontemplasi atas alam semesta”—pada akhirnya menarik batas antara Ada dan Waktu, antara yang konstan dan yang dapat berubah.
Dalam konteks inilah ontologi lahir sebagai cara para filsuf untuk berteori tentang segala sesuatu yang esensi dalam kosmos—untuk merayakan “inti” dari semua realitas, yang tetap dan tidak berubah.
Jadi dalam sejarah “pemurnian pengetahuan dari kepentingan” di Yunani kuno, ontologi merupakan jalan pertama yang ditempuh filsafat untuk mengubur mitis. Melalui ontologi, teori menjauhkan diri dari segala sesuatu yang empiris dan subjektif, karena keduanya dianggap sebagai elemen yang imanen.
Melalui ontologi pula dalam menempuh jalur theoria seorang teoretikus harus menganut “sikap teoretis murni” menekan perasaan subjektif dan kontemplasi bebas dari kepentingan—untuk mengalami momen katarsis yang dicapai melalui, seolah-olah terbebas dari kehendak manusia.
Dengan kata lain, seorang teoretikus, dipaksa untuk menekan kepentingannya demi mengusahakan kepentingan yang lain. Jalur theoria, yang sebelumnya inheren dalam tindakan praksis manusia, kini telah bertransformasi menjadi theoria yang bebas dari kepentingan manusia (pengetahuan yang tidak memihak), yang dengan gagah disebut sebagai “pengetahuan murni”.
Hadirnya Abad Pertengahan
Pemisahan antara pengetahuan dan kepentingan lalu dimanfaatkan oleh ilmu modern Abad Pertengahan, khususnya pemikiran rasionalis dan empiris. Melalui landasan epistemologis kedua aliran ini, ilmu modern sebagai theoria menjadi semakin jauh dari tindakan praksis. Kesenjangan antara teori dan praktik menjadi sulit didamaikan, sehingga teori ilmiah modern nyaris kehilangan sifat emansipatorisnya.
Bahkan, dengan dalih independensi dan objektivitas, para ilmuwan melepaskan diri dari peran sosialnya dan menganggap implementasi hasil penelitian bukan lagi tanggung jawab mereka. Singkatnya, tugas ilmuwan mereproduksi pengetahuan, hasilnya bukan urusan dan tanggung jawab mereka.
Berdasarkan prinsip “ilmu bebas kepentingan”, para ilmuwan berusaha menghindari tanggung jawab atas pengetahuan yang mereka hasilkan sehingga menyisakan keganjilan. Sikap ini malah menjerumuskan ilmu modern ke dalam kepentingan kuasa baru yang menstruktur menjadi bagian dari aparatus oligarki.
Dengan demikian, bentuk kuasa ini mencakup “struktur kuasa negara”, “struktur politik demokrasi liberal”, dan “struktur ekonomi kapitalisme”. Singkatnya di bawah ketiga struktur kuasa ini, ilmu modern berfungsi sebagai basis epistemologis bagi reproduksi pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan ilmuan menjadi “pelayan” kepentingan penguasa dan pemodal.

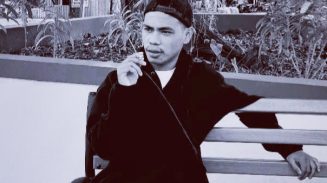
















Tinggalkan Balasan